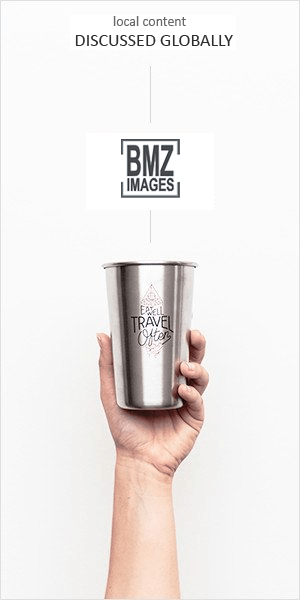PALU, beritapalu.ID | Senja Senin (29/9/2025) mulai merayap ketika puluhan anak muda berkumpul di Ruang Terbuka Hijau Kalikoa. Kawasan kuliner bantaran Sungai Palu itu ramai seperti biasa, tapi kelompok ini punya agenda berbeda. Mereka bukan datang untuk menikmati gorengan dan kopi sore. Sepatu kets terikat rapat, botol minum siap di tangan, dan mata berbinar penuh rasa ingin tahu. Ini adalah walking tour—sebuah pelayaran kaki menyusuri jejak sejarah Kota Palu yang hampir terlupakan.
Anto Herianto, ketua Komunitas Historia Sulteng, berdiri di depan rombongan dengan senyum ramah. Pria yang akrab disapa Anto ini akan menjadi pemandu perjalanan sore itu. Bukan sekadar jalan-jalan biasa, walking tour kali ini adalah upaya menghidupkan kembali memori kolektif sebuah kota yang tumbuh dari kampung kecil di tepi sungai menjadi ibu kota provinsi.
“Kita akan menyusuri tempat-tempat yang mungkin kalian lewati setiap hari, tapi tidak pernah tahu ceritanya,” ujar Anto membuka acara. Para peserta, mayoritas perempuan muda, mengangguk antusias. Mereka siap untuk menemukan Palu yang lain—Palu yang tersembunyi di balik gedung-gedung tua, tiang listrik usang, dan jembatan yang telah berdiri setengah abad.
Jembatan Satu: Saksi Bisu Transformasi Kota
Langkah pertama membawa rombongan ke Jembatan Satu, struktur ikonik yang membentang di atas Sungai Palu. Dari kejauhan, jembatan ini terlihat biasa saja—beton kokoh yang menghubungkan dua sisi kota. Tapi begitu Anto mulai bercerita, aura kebiasaan itu luruh.
“Jembatan ini diresmikan pada 21 Oktober 1976 oleh Wakil Presiden Sri Sultan Hamengkubuwono IX,” kata Anto, suaranya mantap melawan kebisingan kendaraan yang berlalu lalang. Para peserta langsung mengeluarkan ponsel, memotret struktur yang kini terlihat istimewa di mata mereka.
Namun cerita tidak berhenti di sana. Anto melanjutkan dengan nada yang lebih serius, “Jembatan ini pertama kali dirintis oleh para tahanan politik sekitar tahun 1966.” Hening sejenak. Informasi itu menggantung di udara sore, membawa beban sejarah yang tidak ringan.
Jembatan Satu bukan sekadar infrastruktur. Ia adalah cerminan dari aplikasi teknologi konstruksi teranyar pada masanya, sekaligus menjadi saksi bisu bagaimana tenaga paksa menjadi bagian dari pembangunan di era yang kelam. “Jembatan I bukan sekadar penghubung,” Anto menekankan, “tapi saksi bisu bagaimana Palu tumbuh dari kampung kecil jadi kota provinsi.”
Beberapa peserta mengangguk perlahan, mencerna kompleksitas sejarah yang baru saja terurai. Ada yang berbisik pada teman di sebelahnya, ada yang terdiam merenung. Inilah yang terjadi ketika ruang publik diberi konteks—ia berubah dari sekadar tempat lewat menjadi ruang bercerita.

Taman Hiburan Umum: Nostalgia yang Terabaikan
Perjalanan dilanjutkan ke Kelurahan Ujuna, menuju kawasan yang dulunya bernama Taman Hiburan Umum (THU). Luas areanya mencapai 200 x 200 meter persegi, meski kini sulit membayangkan kemegahan masa lalunya. Gedung-gedung tua berdiri dengan cat mengelupas, sebagian bangunan sudah beralih fungsi.
Eja, pemandu lain yang bergabung, mengambil alih narasi. “Kawasan ini dibangun sekitar tahun 1920-an. Bayangkan, ini adalah pusat hiburan di zaman kolonial,” katanya sembari menunjuk ke bagian belakang gedung yang dulunya menjadi barak para karyawan.
“Sudah empat kali kepemilikan kawasan ini berpindah. THU ini masih beroperasi hingga akhir tahun 1990-an,” tambah Eja. Bagi sebagian besar peserta yang lahir di era 2000-an, informasi ini terasa seperti dongeng. Mereka mencoba membayangkan bagaimana kakek-nenek mereka mungkin pernah berdansa atau menonton pertunjukan di tempat yang kini tampak sepi dan terlupakan.
Taman Hiburan Umum adalah potret geliat kehidupan sosial Palu pada masa lalu. Di sinilah masyarakat berkumpul, tertawa, dan menciptakan kenangan bersama. Kini, tanpa upaya pelestarian yang serius, tempat ini hanya akan menjadi catatan kaki dalam buku sejarah yang jarang dibaca.

Rumah Sakit yang Menjelma Pertokoan
Menyeberang ke Jalan Hasanuddin, rombongan berhenti di depan deretan pertokoan yang ramai. Toko-toko modern dengan papan nama mencolok berdiri rapat. Tidak ada yang mengira bahwa di tempat inilah dulunya berdiri sebuah rumah sakit.
“Ini dulunya adalah rumah sakit di zaman penjajahan,” kata Anto. Sejumlah peserta saling menatap, hampir tidak percaya. Ekspresi skeptis terpancar jelas di wajah mereka.
Anto kemudian menjelaskan dengan detail. RSUD Anutapura pertama kali didirikan pada tahun 1922 di lokasi tersebut. Awalnya berstatus sebagai Balai Pengobatan, dibangun atas swadaya masyarakat dan ditangani oleh tenaga paramedis Belanda serta lokal. Setelah kemerdekaan, fasilitas ini diambil alih oleh Pemerintah Daerah Tingkat II Donggala dan menjadi rumah sakit umum.
Namun seiring perkembangan kota dan kebutuhan ruang perdagangan yang terus meningkat, wilayah rumah sakit lama di Jalan Hasanuddin dialihfungsikan menjadi pusat pertokoan. RSUD Anutapura kemudian dipindahkan ke Jalan Kangkung No. 1 pada tahun 1980, lokasi yang masih digunakan hingga sekarang.
“Pemindahan dan pembangunan rumah sakit baru dimulai pada 22 Februari 1980 dan diresmikan pada 4 April 1981 oleh Menteri Kesehatan RI,” Anto menambahkan. Begitu fakta-fakta ini disampaikan, raut wajah peserta berubah dari skeptis menjadi takjub. Mereka mulai memahami bahwa kota ini memiliki lapisan sejarah yang tebal, tersembunyi di balik permukaan modernitas.

Tiang Listrik Monumental dan Toko Kaset Legendaris
Di depan Kantor Bank Sulteng, Anto melakukan sesuatu yang tidak biasa. Ia hampir membenturkan tubuhnya ke salah satu tiang listrik berbahan kayu ulin. Tindakan teatrikal itu berhasil menyentakkan peserta. Semua mata tertuju pada tiang tua yang berdiri kokoh.
“Ini yang tersisa dan masih utuh. Satunya ada juga di Kampung Lere, tapi tidak utuh lagi, sudah terpotong,” jelas Anto. Tiang itu awalnya adalah tiang kabel telepon, namun beralih fungsi menjadi tiang listrik sejalan dengan perkembangan jaringan kelistrikan.
“Di sini, lebih dulu masuk jaringan telepon daripada jaringan listrik,” tambahnya. Informasi sederhana itu membuka perspektif baru tentang bagaimana teknologi komunikasi dan energi berkembang di Palu. Kota ini punya ritme pertumbuhannya sendiri, tidak selalu mengikuti pola yang sama dengan kota-kota besar lainnya.
Tepat di belakang tiang bersejarah itu, Anto menunjuk sebuah toko jadul yang menjual aneka kaset musik tempo dulu. Toko ini masih bertahan hingga kini, menjadi relik hidup dari era analog. “Anak-anak muda zaman 1970-an sampai 1990-an tidak ada yang tidak tahu toko ini,” kata Anto dengan nada nostalgia. “Sampai sekarang masih menjual koleksi-koleksi lagu dalam pita kaset.”
Beberapa peserta tertawa, sebagian lagi penasaran dan langsung mendekati toko untuk melihat-lihat. Bagi generasi yang tumbuh dengan Spotify dan musik digital, kaset adalah benda asing yang menarik.

Rumah Raja dan Sekolah Pribumi
Di sebelah toko kaset, kini berdiri sebuah apotek. Tidak banyak yang tahu bahwa tempat itu dulunya adalah kediaman salah satu Raja Palu, yaitu Tjatjo Ijazah. Ia memerintah sebagai Raja Palu pada periode 1949–1950, salah satu raja terakhir dalam sistem monarki Kerajaan Palu sebelum sepenuhnya bergabung dengan Republik Indonesia.
Pemerintahan Tjatjo Ijazah berlangsung setelah masa Djanggola (1921–1945), dan menandai transisi menuju sistem pemerintahan modern di Sulawesi Tengah. “Bayangkan, di tempat ini dulunya ada istana kecil, tempat keputusan-keputusan penting diambil,” ujar Anto.
Menyeberang ke Jalan Togean, langkah terakhir membawa rombongan ke SDN 1 Palu. Sekolah ini memiliki cikal bakal yang sangat penting dalam sejarah pendidikan di Palu. Didirikan pada awal abad ke-20 oleh pemerintah Hindia Belanda sebagai bagian dari kebijakan Ethische Politiek (Politik Etis), sekolah ini awalnya dikenal sebagai Hollandsch-Inlandsche School (HIS) Palu.
HIS Palu adalah sekolah dasar berbahasa Belanda untuk anak-anak pribumi terpilih. Ia menjadi tempat pendidikan bagi anak-anak bangsawan lokal, tokoh adat, dan elite birokrasi awal. Lulusan HIS banyak yang kemudian melanjutkan ke MULO (setara SMP) atau menjadi pegawai kolonial dan tokoh pergerakan lokal.
Setelah Indonesia merdeka, sekolah ini berganti nama menjadi SD Negeri 1 Palu dan tetap beroperasi di lokasi yang sama. Bangunan asli bergaya kolonial masih digunakan hingga dekade 1990-an sebelum direnovasi. SDN 1 Palu menjadi simbol transisi dari pendidikan kolonial ke pendidikan nasional di Sulawesi Tengah.

Pertanyaan Kritis di Penghujung Tur
Senja telah berganti malam ketika rombongan kembali ke titik awal di RTH Kalikoa. Tapi perjalanan belum benar-benar selesai. Para peserta, yang sepanjang tur terlihat antusias, kini berubah menjadi lebih kritis. Pertanyaan demi pertanyaan dilontarkan kepada Anto dan Eja.
Salah satu pertanyaan yang paling menohok datang dari seorang peserta perempuan, “Kenapa Pemerintah Kota Palu tidak berusaha melestarikan bangunan-bangunan yang punya nilai historis itu?”
Anto terdiam sejenak, kemudian tersenyum tipis. “Suatu hari kalau kamu jadi pemimpin kota ini, mungkin ini yang perlu kamu wujudkan,” jawabnya diplomatis.
Jawaban itu bukan pelarian dari tanggung jawab, melainkan undangan. Undangan bagi generasi muda untuk tidak hanya mengkritik, tapi juga mengambil peran aktif dalam pelestarian sejarah kotanya. Walking tour bukan hanya tentang masa lalu, tapi juga tentang masa depan—tentang siapa yang akan menjaga ingatan kolektif ini agar tidak lenyap ditelan pembangunan.
Ketika peserta mulai berpamitan dan berpencar, ada yang berubah dalam cara mereka memandang kota. Jalan yang mereka lalui setiap hari kini tidak lagi sama. Jembatan, toko, bahkan tiang listrik tua—semuanya berbicara. Dan mereka, untuk pertama kalinya, benar-benar mendengarkan. (bmz)

 pojokPALU
pojokPALU
 pojokSIGI
pojokSIGI
 pojokPOSO
pojokPOSO
 pojokDONGGALA
pojokDONGGALA
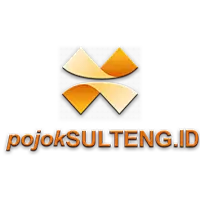 pojokSULTENG
pojokSULTENG
 bisnisSULTENG
bisnisSULTENG
 bmzIMAGES
bmzIMAGES
 rindang.ID
rindang.ID













 Akurat dan Terpecaya
Akurat dan Terpecaya