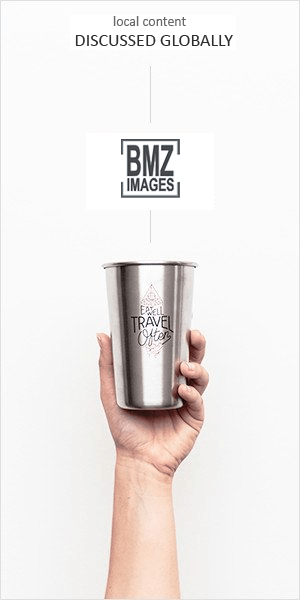PALU, beritapalu.ID | Hujan gerimis baru saja membasahi Jalan Abdul Raqi, Palu Barat. Di tengah reruntuhan yang masih tersisa, puluhan seniman berkumpul dengan spanduk-spanduk yang mencolok mata. “Gedung ini dijual tanpa perantara,” bunyi salah satu spanduk yang dibentangkan di depan gedung pertunjukan dua lantai yang masih berdiri kokoh meski kondisinya rusak parah. Spanduk lain bertulisan lebih sinis: “Dijual Cepat Tanpa Ta Colo” dan “Kawasan ini akan dibangun Rumah Impian Seniman Budayawan, Silakan Kapling.”
Sabtu sore, 27 September 2025—tujuh tahun setelah tsunami menerjang Palu—puluhan seniman berkumpul di sisa-sisa Taman Budaya Sulawesi Tengah. Mereka tidak datang untuk bernostalgia, melainkan untuk memprotes. Protes terhadap pemerintah yang dianggap mengabaikan nasib ruang seni yang dulu menjadi jantung kebudayaan di kota ini.
“Sekecil apapun tetap rumah kami Taman Budaya,” tulis spanduk lain yang dipasang dengan penuh emosi. Kalimat sederhana itu merangkum kerinduan mendalam para seniman terhadap ruang yang telah hilang selama bertahun-tahun.
Jejak yang Tersapu Tsunami
Taman Budaya Palu dulunya membentang hampir lima hektare di pesisir Teluk Palu. Lokasinya strategis, tepat di tepi laut yang memberikan panorama indah bagi setiap pertunjukan dan pameran seni. Namun posisi inilah yang kemudian menjadi malapetaka ketika gelombang tsunami setinggi 4-7 meter menyapu kawasan ini pada 28 September 2018.
Dalam hitungan menit, panggung yang sering menjadi saksi festival musik, galeri seni yang memamerkan karya seniman lokal, dan berbagai ruang pertunjukan hancur lebur. Yang tersisa hanya gedung pertunjukan dua lantai yang kini berdiri seperti saksi bisu kehancuran, dengan dinding retak dan lantai yang ambruk di beberapa bagian.
“Hampir seluruh bangunan ambruk, kecuali gedung pertunjukan yang masih berdiri meski kondisinya berantakan,” kenang salah seorang seniman yang menyaksikan langsung kehancuran itu. Kawasan yang dulu ramai dengan aktivitas seni kini menyusut menjadi sekitar dua hektare, sebagian lahannya bahkan sudah beralih fungsi.
Antara Zona Merah dan Hak Berkesenian
Ketua Dewan Kesenian Sulawesi Tengah (DKST) Hapri Ika Poigi yang hadir dalam aksi protes itu mengaku tidak mengerti mengapa Taman Budaya tidak dibangun kembali pascabencana. Kebingungan serupa dirasakan Emhan Saja, salah seorang seniman yang mempertanyakan inkonsistensi pemerintah.
“Kalau disebut karena berada di zona merah, lalu kenapa UIN Datokarama di sebelah tetap bisa dibangun?” tanya Emhan dengan nada kecewa. Pertanyaan ini menyentuh inti permasalahan: standar ganda dalam penerapan zonasi risiko bencana.
Secara teknis, lokasi Taman Budaya memang berada di zona merah tsunami berdasarkan kajian BNPB dan Peta Rawan Bencana Kota Palu. RTRW Kota Palu 2010-2030 menetapkan kawasan ini sebagai zona terbatas untuk pembangunan permanen. Pejabat Dinas PUPR pernah menyatakan, “Kami tidak bisa membangun kembali di zona yang secara teknis tidak aman.”
Namun, alasan teknis ini tidak menjawab pertanyaan fundamental para seniman: mengapa prioritas rehabilitasi tidak pernah memasukkan ruang budaya dalam skema pemulihan? Pemerintah memang memprioritaskan infrastruktur vital seperti Jembatan Palu IV, jalan nasional, huntap, dan fasilitas pendidikan. Bantuan donor internasional seperti JICA pun difokuskan pada infrastruktur transportasi dan mitigasi bencana.

Seniman yang Luntang-Lantung
Adi Tangkilisan, seniman lain yang ikut dalam aksi protes, menggambarkan dampak hilangnya Taman Budaya dengan sangat personal. “Ketiadaan Taman Budaya membuat sebagian seniman tidak punya tempat untuk mengekpresikan diri dan bakatnya. Pascabencana, seniman di daerah ini luntang lantung mencari ruang untuk menyatakan keberadaannya.”
Kata “luntang lantung” yang digunakan Adi merefleksikan kondisi eksistensial para seniman Palu. Mereka tidak hanya kehilangan gedung, tetapi kehilangan identitas kolektif. Festival budaya, pertunjukan musik, dan pameran seni yang dulu rutin digelar kini terpaksa berpindah ke ruang-ruang alternatif seperti kampus, kafe, dan taman kota—ruang-ruang yang tidak memiliki karakter khusus untuk seni.
“Ini sangat serius. Seniman juga warga negara, rakyat Indonesia yang punya hak-hak juga, sama seperti warga negara lainnya,” ucap seorang seniman dengan geram. Kemarahan ini bukan sekadar soal bangunan, tetapi soal pengakuan terhadap eksistensi dan kontribusi seniman dalam masyarakat.
Tenda Diskusi dan Suara yang Tidak Padam
Tidak puas dengan membentangkan spanduk, puluhan seniman mendirikan tenda dan menggelar diskusi kecil. Mereka berbagi cerita, merencanakan aksi lanjutan, dan yang paling penting, mempertahankan semangat berkesenian meski tanpa panggung permanen.
“Sepertinya hanya Taman Budaya ini yang tidak dibangun kembali, sementara fasilitas publiknya sudah berdiri megah sejak bencana lalu,” timpal seorang seniman. Frustrasi itu memuncak ketika salah seorang di antara mereka berteriak, “Bullshit!”—ekspresi kekecewaan yang melampaui kesantunan berbahasa.
Namun di balik kemarahan itu, ada tekad yang tidak padam. Seperti yang pernah diucapkan seorang seniman Palu dalam diskusi komunitas tahun 2020: “Kami kehilangan panggung, tapi tidak kehilangan suara.”
Ruang Simbolik yang Belum Pulih
Taman Budaya Palu bukan sekadar bangunan yang hilang. Ia adalah ruang simbolik yang menyimpan jejak seni, komunitas, dan kebersamaan. Ketidakhadirannya pascabencana mencerminkan tantangan pemulihan yang tidak hanya fisik, tetapi juga kultural.
Beberapa komunitas kini mendorong agar Taman Budaya dibangun kembali di lokasi baru yang lebih aman, misalnya di zona hijau Palu Barat atau Palu Selatan. Usulan ini belum masuk dalam RPJMD 2025-2029, tetapi bisa menjadi bagian dari agenda pemulihan sosial dan budaya jangka panjang.
Aksi protes di sore yang mendung itu menjadi pengingat bahwa resiliensi sebuah kota tidak hanya diukur dari infrastruktur fisik yang pulih, tetapi juga dari kemampuannya memberikan ruang bagi jiwa dan kreativitas warganya. Jika Palu ingin menjadi kota yang benar-benar pulih, maka pemulihan ruang budaya harus menjadi bagian integral dari narasi besar itu.
Sore beranjak remang ketika para seniman itu mulai merecoki dengan diri dengan gorengan plus tahu campur tempe, tetapi spanduk-spanduk protes tetap terpasang. Seperti janji bahwa suara mereka akan terus bergema, menunggu jawaban dari pemerintah yang selama ini tak terdengar. (bmz)

 pojokPALU
pojokPALU
 pojokSIGI
pojokSIGI
 pojokPOSO
pojokPOSO
 pojokDONGGALA
pojokDONGGALA
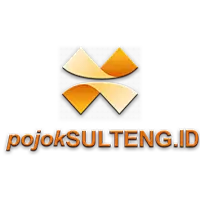 pojokSULTENG
pojokSULTENG
 bisnisSULTENG
bisnisSULTENG
 bmzIMAGES
bmzIMAGES
 rindang.ID
rindang.ID













 Akurat dan Terpecaya
Akurat dan Terpecaya