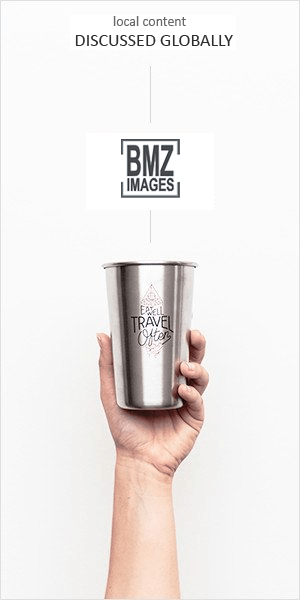SEHARUSNYA sejak awal perdebatan tentang “Tanah Negara” yang “dicuitkan” oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid, para Mahasiswa Fakultas Hukum mengisi ruang-ruang kritik dan debat tentang topik ini. Inilah momen untuk mempelajari tentang Land Reform dan semangat yang terkandung di dalamnya.
Mahasiswa Fakultas Hukum seharusnya belajar banyak tentang teori-teori Kelas yang dikembangkan oleh Karl Marx atau paling tidak Max Weber.
Sayangnya, Mahasiswa Fakultas Hukum pasca Gerakan Reformasi, jarang mau membaca dan mempelajari Teori Kelas ini, padahal bisa mempelajari bagaimana masyarakat terbagi menjadi kelompok-kelompok berdasarkan kepemilikan alat produksi, kekayaan, status sosial, dan kekuasaan. Marx berfokus pada konflik antara kelas pemilik modal (Borjuasi) dan kelas pekerja (Proletariat).
Mahasiswa Fakultas Hukum paling tidak harus memiliki pengetahuan tentang penguasaan alat produksi itu—yang akan mengantarnya pada pengetahuan tentang terciptanya hukum dan posisi hukum sebenarnya untuk Borjuasi atau Proletariat.
Kembali tentang aturan tentang Tanah Absentee sebenarnya sudah ada sejak lama, bukan hal baru di republik ini—apalagi kalau itu seakan-ada “Ide cerdas Menteri ATR/BPN.
Tanah Absentee sendiri selama ini dikenal dengan istilah tanah terlantar. Dalam Undang-undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA). Undang-undang yang menandai Reforma Agraria atau Land Reform di republik ini.
UUPA ini kalau di tangan orang benar, maka akan sangat bermanfaat sekali. Sayangnya, tanah terlantar ini hanyalah sebuah kutipan oleh Menteri ATR/BPN dari Nusron, di berbagai media massa, pernyataannya yang belakangan jadi sorotan, sebenarnya ia ingin menjelaskan maksud Pasal 33 Ayat 3 UUD 1945 berkaitan dengan kebijakan pemerintah atas tanah terlantar.
Padahal Tanah Absentee itu sendiri diatur dalam berbagai peraturan: Pasal 10 ayat (1) UUPA yang berbunyi: “Setiap orang dan badan hukum yang mempunyai sesuatu hak atas tanah pertanian pada asasnya diwajibkan mengerjakan atau mengusahakannya sendiri secara aktif, dengan mencegah cara-cara pemerasan.”
Aturan lain yang mengaturnya adalah: Pasal 3d Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1964 tentang Perubahan dan Tambahan Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian (“PP 41/1964”) menjelaskan mengenai larangan kepemilikan tanah absentee, yang bunyinya sebagai berikut: “Dilarang untuk melakukan semua bentuk pemindahan hak baru atas tanah pertanian yang mengakibatkan pemilik tanah yang bersangkutan memiliki bidang tanah di luar Kecamatan di mana ia bertempat tinggal.”
Ada 4 dasar hukum yang mengatur tentang Tanah Absentee:
Pertama, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
Kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1964 tentang Perubahan dan Tambahan Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian;
Ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1977 tentang Pemilikan Tanah Pertanian Secara Guntai (Absentee) Bagi Para Pensiunan Pegawai Negeri;
Keempat, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.
Bila dicermati dengan baik, maka UUPA sendiri merupakan semangat Land Reform. Dimana ada redistribusi tanah terlantar kepada para petani yang tidak memiliki tanah. Ringkasnya, aturan ini melarang para Tuan Tanah (Land Lord) untuk mendominasi penguasaan tanah yang akan merugikan para petani lokal—atau sebut saja petani miskin.
Land Reform sendiri bisa diartikan: dalam hukum agraria adalah: serangkaian tindakan yang bertujuan untuk merombak struktur penguasaan, pemilikan, dan penggunaan tanah, dengan fokus pada redistribusi tanah kepada petani kecil dan buruh tani, serta penataan kembali hubungan agraria yang lebih adil dan merata.
Land Reform juga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama petani yang tidak memiliki tanah, serta menciptakan keadilan sosial dalam pengelolaan sumber daya agraria.
Dalam Land Reform sendiri meliputi: redistribusi tanah, penataan kembali penguasaan tanah, penataan penggunaan tanah, peningkatan kesejahteraan petani.
Namun sayangnya, Menteri ATR/BPN tidak melandaskan argumentasinya pada semangat Land Reform dalam UUPA tersebut. Dia lebih memilih untuk melandaskan argumentasinya pada Pasal 33 Ayat 3 UUD 1945 berkaitan dengan kebijakan pemerintah atas tanah terlantar. Pasal itu menyebut, bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai negara, digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Tidak menyebut sama sekali tentang semangat Reforma Agraria.
Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah. Pasal 1 berbunyi: “Tanah adalah permukaan bumi baik berupa daratan maupun yang tertutup air, termasuk ruang di atas dan di dalam tubuh bumi, dalam batas tertentu yang penggunaan dan pemanfaatannya terkait langsung maupun tidak langsung dengan penggunaan dan pemanfaatan permukaan bumi”.
Pasal 2 berbunyi: “Tanah Negara atau Tanah yang dikuasai Langsung oleh Negara adalah Tanah yang tidak dilekati dengan sesuatu hak atas tanah, bukan Tanah wakaf, bukan Tanah Ulayat dan/atau bukan merupakan aset barang milik negara barang milik daerah”.
Sayangnya, dalam beberapa kasus mencolok belakangan ini tentang penguasaan tanah dengan barbar, seperti kasus pagar laut diberabagai daerah, Menteri ATR/BPN pun seakan-akan tidak bisa berkutik menghadapi Kaum Borjuasi Nasional—alih-alih berani berpihak pada nelayan miskin yang tidak memiliki alat produksi.
Seharusnya Menteri ATR/BPN sejak awal menjelaskan apa yang dia maksud Tanah Terlantar yang tujuannya adalah redistribusi tanah untuk para Petani Miskin—tentu saja akan mendapat dukungan masyarakat luas.
Sayangnya, argumentasinya sejak awal sudah salah, dimana seolah-olah dia menggambarkan negara ini adalah negara sosialis, dimana peran dan kekuasaan negara tentang aset kepemilikan memang lebih dominan dibanding kepemilikan pribadi.
Karena gagap dalam logika berpikir, landasan hukum dan argumentasinya—akhirnya Menteri ATR/BPN seakan-akan menjadi seorang sosialis malu-malu dan bersemangatkan Land Reform sejati. ***
*) Penulis adalah praktisi hukum.

 pojokPALU
pojokPALU
 pojokSIGI
pojokSIGI
 pojokPOSO
pojokPOSO
 pojokDONGGALA
pojokDONGGALA
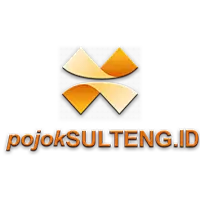 pojokSULTENG
pojokSULTENG
 bisnisSULTENG
bisnisSULTENG
 bmzIMAGES
bmzIMAGES
 rindang.ID
rindang.ID



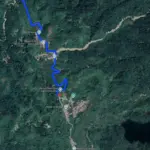









 Akurat dan Terpecaya
Akurat dan Terpecaya