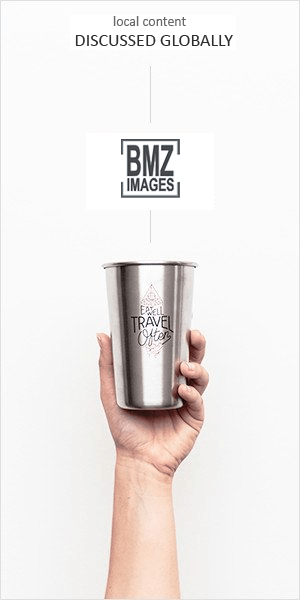PALU, beritapalu.ID | Sebagai produsen nikel terbesar dunia dengan porsi 54–61 persen dari pasokan global—yang diproyeksikan naik hingga 74 persen pada 2028—Indonesia berada di garda depan transisi energi hijau. Namun, di balik kemilau hilirisasi industri, mengemuka ancaman serius yang jarang tersorot: limbah beracun dari pengolahan nikel yang berpotensi merusak lingkungan dan membahayakan kesehatan masyarakat.
Ancaman tersebut kian nyata di kawasan Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), Sulawesi Tengah, salah satu pusat pengolahan nikel terbesar di Asia. Di sana, risiko pencemaran air dan udara, deforestasi, kerusakan ekosistem pesisir, konflik lahan, hingga kecelakaan kerja terus meningkat seiring ekspansi industri nikel.
Dua insiden besar terjadi dalam satu pekan pada Maret 2025. Pada 16 Maret, bendungan tailing milik PT Huayue Nickel Cobalt jebol, mencemari aliran Sungai Bahodopi. Enam hari berselang, longsor menimpa fasilitas pengolahan milik PT QMB New Energy Material, menewaskan tiga pekerja.
“Kedua peristiwa ini mengungkap lemahnya tata kelola dan pengawasan di sektor pertambangan nikel,” tegas Anto Sangaji, Peneliti Auriga Nusantara untuk Ekonomi dan Lingkungan (AEER), dalam konferensi pers daring, Rabu (13/8/2025).
Proses pengolahan bijih nikel jenis limonite—yang kadar nikelnya rendah (0,8–1,5%)—menggunakan metode High Pressure Acid Leaching (HPAL) untuk menghasilkan mixed hydroxide precipitate (MHP), bahan baku baterai listrik. Namun, proses ini menghasilkan limbah dalam jumlah sangat besar.
“Hanya sekitar 1% dari bijih limonite yang menjadi produk bernilai ekonomi. Sisanya, 99%, berubah menjadi limbah tailing,” ungkap Pius Ginting, Direktur Eksekutif AEER. Ia menekankan, pengelolaan limbah inilah yang harus menjadi perhatian serius publik dan regulator.
Bahaya bertambah ketika teknologi penanganan tailing di Indonesia masih berisiko tinggi. Menurut Steven H. Emerman, Ph.D., ahli geofisika dan hidrologi tambang dari Amerika Serikat, tailing di Indonesia masih mengandung air hingga 35 persen. “Dengan kondisi geologi tanah vulkanik yang labil, ditambah potensi gempa dan curah hujan ekstrem, bendungan penampung tailing sangat rentan longsor,” katanya.
Ia menambahkan, standar teknis global harus disesuaikan dengan realitas geografis dan iklim Indonesia. “Fakta di lapangan menunjukkan sejumlah fasilitas sudah kolaps, mencemari sungai dan laut. Ini bukan isu teknis semata, tapi soal keselamatan publik.”
Data dari jurnal Nature mencatat, sejak 1915 telah terjadi 257 kegagalan bendungan tailing di seluruh dunia, menewaskan 2.650 orang. Jumlah insiden meningkat signifikan pasca-2000, seiring melonjaknya permintaan nikel untuk baterai kendaraan listrik.
Ironi lain diungkap Rini Astuti, Peneliti dari Asia Research Center Universitas Indonesia. “HPAL memang sukses mengubah bijih rendah kadar menjadi komoditas bernilai tinggi. Tapi dampak lingkungannya sangat besar dan membutuhkan pengawasan ekstra ketat,” ujarnya.
Dalam satu dekade (2013–2023), produksi nikel Indonesia melonjak 920 persen. Namun, untuk setiap satu ton nikel yang dihasilkan, terbentuk 110 ton limbah tailing. “Jika tata kelolanya tidak siap, ini akan jadi bom waktu lingkungan,” kata Rini.
Ia juga menyoroti aspek non-teknis: stabilitas politik, tingkat korupsi, kebebasan berpendapat, dan kebijakan iklim yang kontekstual menjadi kunci keberhasilan pengelolaan industri hijau.
Untuk mengangkat isu ini ke ruang publik, AEER bekerja sama dengan TEMPO TV meluncurkan film dokumenter berjudul “Limbah Nikel dan Mimpi Energi Bersih”. Film ini akan tayang perdana di kanal YouTube Tempo TV pada 15 Agustus 2025, menampilkan bukti visual dari masyarakat terdampak, serikat pekerja, akademisi, dan aktivis lingkungan.
Rekaman mencakup air sungai yang terkontaminasi logam berat, tumpukan tailing rawan longsor, hingga kisah pekerja yang kehilangan nyawa. Salah satu gambaran paling menggugah: warga yang terpaksa hidup berdampingan dengan pabrik nikel, bahkan ada yang lahannya kini terkurung di balik pagar seng kawasan IMIP.
“Kami verifikasi langsung kedekatan narasumber dengan proyek tambang dan besarnya dampak yang mereka alami,” kata George William Piri dari Tempo TV. “Ini ironi keamanan di pusat industri nikel terbesar di Asia.”
Peluncuran film ini bertepatan dengan Annual Indonesia Green Industry Summit (AIGIS) 2025 (20–22 Agustus) di Jakarta, yang mengusung tema dekarbonisasi dan industri hijau. Film ini menjadi peringatan kuat: transisi energi tidak boleh mengorbankan rakyat kecil dan kelestarian alam.
Dengan tagline “Energi Bersih Harus Adil”, dokumenter ini mengajak pembuat kebijakan, pelaku industri, dan masyarakat luas untuk memastikan bahwa masa depan hijau Indonesia dibangun di atas prinsip keadilan ekologis dan sosial, bukan hanya target ekonomi semata. (afd/*)

 pojokPALU
pojokPALU
 pojokSIGI
pojokSIGI
 pojokPOSO
pojokPOSO
 pojokDONGGALA
pojokDONGGALA
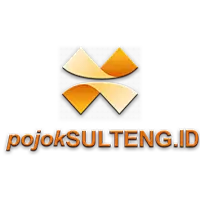 pojokSULTENG
pojokSULTENG
 bisnisSULTENG
bisnisSULTENG
 bmzIMAGES
bmzIMAGES
 rindang.ID
rindang.ID













 Akurat dan Terpecaya
Akurat dan Terpecaya